Lelaki itu telah cukup lama merajai sungai, dalam penggalan masa hidupnya.
Sungai dan dirinya ibarat kacang menaungi kulit. Ia telah begitu lama menundukkan aliran sungai, lebih dari perempat masa usianya sendiri. Telah sejak ia bergelar remaja, saat orang-orang mulai memanggilnya si raja sungai. Si Wan si raja sungai, panggilan yang terasa cukup disegani bagi masyarakat penghuni desa sekitar sungai itu. Wan tak hanya pakar menundukkan deras arus sungai, ia malahan telah diberi kepercayaan memimpin berbagai acara-acara suku warga Rumbio. Amanah mulia yang menurutnya sangat langka diberikan kepada orang, hanya mereka-mereka yang terpilih.
Inilah pekerjaan Wan, setiap hari ia berjuang menjaga rakit di tepi sungai. Mengantar dan menjemput warga yang hendak pergi dan pulang ke kampung. Sebab desa mereka dengan kota dipisahkan oleh hamparan sungai yang terkadang sering meluap saat musim hujan. Meski tak sebegitu jauh jaraknya, namun rakit tetap dibutuhkan. Sama seperti Wan membutuhkan uang hasil bayaran para penyewa rakit untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Wan menekuni pekerjaannya, setahun lalu ia ditawari pekerjaan sebagai penjaga kebun sawit seorang pengusaha kaya asal Pekanbaru, tapi dengan santun ia tolak. Baginya menjadi raja sungai adalah kerja tak ternilai. Mungkin lebih mulia dari sekeping emas. Saat kau berharga di tengah orang ramai, maka saat itulah hidupmu akan bahagia, Wan punya prinsip itu. Mungkin kurang logis di pikiran orang, tapi Wan berjiwa kukuh dan pejuang. Ia merelakan hidupnya menjadi abdi penjaga sungai. Sungai adalah kerajaan tempat ia mengabdi, selamanya.
Sosok Wan cukup dihargai. Bukan dengan uang seribu dua ribu hasil ia menjaga rakit setiap hari, tapi lebih pada sikap warga Rumbio. Semua orang segan padanya, mereka mengikuti semua perintah dan nasehat Wan. Wan si kepala suku, wajarlah jika dapat penghargaan sebegitu. Wan begitu taat pada adat istiadat yang ia anggap warisan leluhur yang harus dilestarikan. Wan selalu mengingatkan warga Rumbio jika ada yang terlihat mulai menyepelekan adat istiadat suku Ocu. Bahkan pada keluarganya, Wan akan tetap berpegang pada tugasnya sebagai seorang kepala suku sekaligus si raja sungai. Ia merasa punya tanggung jawab untuk mengingatkan warga yang dirasa mulai menyimpang.
Ramadhan kurang sepekan
Siang itu Wan telah berdiri di tepi sungai. Ia menautkan tali rakit yang baru saja menepi. Wan mengenakan kaos biru lusuh yang hampir seusia dengannya. Wajahnya berkeringat dibalur garis-garis ketuaan yang mulai membekas di sudut-sudut kulit mukanya. Wan telah cukup lama bekerja di sini, tapi ia tak pernah merasa lelah. Seperti siang itu, di tengah kemuraman raut wajahnya, ia menyisakan sebuah senyuman untuk seorang gadis berusia tanggung. Gadis itu putrinya, ia pulang siang ini dari Pekanbaru. Nama gadis itu Maymunah. Istri Wan memilih pesantren Islamic Boarding School di Pekanbaru sebagai tempat gadis tanggung itu belajar.
“Ayah, sehat?” Maymunah menyalami tangan Wan lalu menciumnya. Gadis tanggung itu dididik di pesantrennya untuk menghargai dan memuliakan orang tua.
“Sehat saja, kau tak kasi kabar dulu mau pulang. Seharusnya ibumu bisa menjemput.”
“Liburan mendadak, Yah.”
“Oh, awal Ramadhan kau di sini ya?”
“Sepertinya begitu.”
Wan tersenyum bahagia. Ia sudah hampir tiga bulan ini tak melihat Maymunah. Maklum lah Maymunah jarang pulang. Kebijakan di pesantrennya mengharuskan Maymunah tak bisa pulang. Hanya pada waktu-waktu tertentu.
“Kau bisa balimau di sini, May” Wan bersuara.
“Mandi balimau maksud, Ayah?”
“Ya, hari sabtu depan kita akan gelar balimau bersama di sini, warga sudah siapkan acara dan hiburannya. Beruntung kau pulang, jadi kita bisa balimau bersama.”
Maymunah menyeringai. Ia tak menyahut. Wan memperhatikan gadis itu, tak biasanya May putrinya mengabaikan ucapannya. Lalu ia menjinjing tas May, membawanya ke tepi sungai. Mungkin May masih lelah, tak seharusnya juga ia berbicara itu di hadapan May yang masih lelah. Yang perlu dilakukannya saat ini adalah mencarikan ojek yang bisa ia percaya untuk mengantarkan May pulang. Putrinya teramat ayu, ditambah balutan busana muslimah yang begitu rapi dan indah. Ia tau pemuda-pemuda di tepi sungai banyak yang mengincarnya. Untung saja May putri Wan, sosok yang disegani. Andai tidak mungkin May telah dirayu oleh pemuda-pemuda di sekitar sungai. Wan tak rela putrinya diganggu oleh pemuda kampung. Ia pun bergegas menghampiri seseorang yang ia percaya untuk mengantarkan May pulang.
“Antarkan langsung ke rumah, jangan macam-macam!” Wan tanpa bicara serius pada salah seorang tukang ojek di tepi sungai. Tukang ojek itu pun tampak segan dan ketakutan. Ia kontan menarik barang bawaan May dan menaikkannya di atas motor.
“May pulang dulu, Yah.”
“Ya, hati-hati, bilang masak yang sedap sama emak!”
Wan kembali ke tepi sungai. Ia membantu beberapa orang yang tampak kesulitan menurunkan motor dari atas kapal rakit. Kapal rakit Wan sederhana saja, tidak mengenakan tenaga mesin. Hanya memanfaatkan arus dan gerak mata angin. Dari tepi sungai ke seberang ditautkan sebuah tali yang terbuat dari baja yang cukup kuat. Lantas rakit yang berukuran sebesar rumah gubuk dikaitkan pada bentangan tali itu. Rakit pun bergerak bebas di sungai mengikuti arus yang membawa ke seberang sungai. Murah namun harus telaten, Wan menggeluti pekerjaan itu telah cukup lama, ia merasa mulia.
Mandi balimau
Ramadhan lusa akan datang. Warga Rumbio sibuk dengan tradisi mandi balimau, yakni mandi bersama di tepi sungai menggunakan jeruk dan wewangian yang dipercaya akan membersihkan diri sebelum memasuki awal Ramdhan. Wan bertugas memimpin tradisi itu, sebab ia kepala suku di situ. Acara telah dipersiapkan sedemikian rupa, lengkap dengan pesta kecil dan hiburan musik yang jauh-jauh didatangkan dari kota Pekanbaru. Mandi balimau tahun ini dirancang cukup meriah dari biasanya. Wan senang karena semua warga membantu dengan setia tugas-tugasnya dalam menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Hanya saja malam ini ia amat kesal dengan Maymunah. Gadis itu menolak disuruh ikut mandi bersama. Ia bahkan menentang rencana ayahnya untuk menyelenggarakan pesta balimau. Menurut May apa yang dilakukan Wan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi balimau lebih membawa pada dampak keburukan. Sebab itulah May menolaknya.
“Ayah tak habis pikir dengan kau ni May, ajaran apa yang kau dapat di pesantrenmu itu? ini tradisi nenek moyang kita, tidak bisa kita menentangnya!”
“Adat itu bukan Islam, Ayah,”
“Tapi menentang adat kau akan kualat, May!”
“Tak ada istilah kualat, Yah.”
“Kalau begitu kau mandi balimau di rumah saja, tak usah ikut ke sungai. Di rumah pakai air sumur di rumah!”
“May tak bisa,Yah.”
“Anak kurang ajar kau dengan adat!” suara Wan meninggi. May menunduk datar. Wan murka, sementara sang ibu hanya bisa mengurut dada. Ia tak tega jika harus bersikap sama pada May seperti Wan. Ia juga tak sanggup jika harus menentang suaminya.
“May ingat apa yang dikatakan oleh Ustadz May di pesantren, mengada-ada sesuatu yang tak ada dalam ajaran Islam dalam hal ibadah termasuk bid’ah Yah. Belum lagi dampak buruk dari balimau itu, Ayah bayangkan saja orang sekampung mandi bersama dengan hiburan musik-musik. Itu salah Yah!”
“Ayah tak suka kau mengajari ayah May! Aku ketua suku di sini, tugasku menjaga adat dan tradisi. Kalau kau tak suka ya sudah, jangan buat kacau acara. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan kau di tengah Ramadhan besok, aku tak mau tanggung jawab.”
“Tak ada kaitannya antara balimau dengan keselamatan manusia.”
“Sudah cukup! Jangan bicara lagi. Kau masih ingusan, jangan coba-coba menasehati orang tua.”
Pesta balimau tetap digelar. May tak datang, Wan pun tak peduli dengan ketidak hadiran putrinya. Wan puas, acara berlangsung sukses. Ia bahagia tugasnya sebagai kepala suku tertunai dengan baik. Tak apalah putrinya menentang, yang pasti semua warga Rumbio mendukung dan menikmati acara yang dilangsungkan. Hanya saja pagi ini, dua hari setelah acara balimau berlangsung, Wan mulai gelisah dengan sebuah kabar yang membuat hatinya khawatir.
“Wan, keluarga kami dari kemarin terjangkit gatal-gatal. Bagaimana ini?” Pak Atan menemui Wan di pagi hari.
“Maksud kau apa?”
“Gara-gara mandi balimau kemarin, kami minta bantuan diobati.”
“Ah, mungkin itu air di sumur kalian yang tercemar.”
“Tidak Wan, keluarga Mak Ijah pun sama, dua putrinya dan Mak Ijah sendiri kena gatal-gatal.”
“Gatal-gatal bagaimana maksudmu?”
“Kulitnya banyak bintik-bintik kecil mengandung air, menjijikkan sekali, mirip kulit katak.”
“Ah, jangan mengada-ada kau, Tan.”
“Tidak Wan, aku serius.”
“Menurutmu apa sebabnya?”
“Mandi balimau itu.”
“Kita tiap tahun mengadakan balimau aman-aman saja. Jangan kaitkan penyakit kalian dengan balimau.”
“Wan, coba kau lihat kesana!” Pak Atan menunjuk jauh ke daerah hulu sungai dengan telunjuk jemarinya.
“Kenapa?”
“Kau tau orang-orang di sana terlalu rakus memanfaatkan sungai. Mereka berlebihan membuang limbah rumah tangga.”
“Ah,..” Wan mendesah resah.
“Lalu?”
“Masih banyak yang akan mengadu padamu soal penyakit kulit ini. Kau harus bersiap-siap Wan.”
“Bersiap-siap apa? Ini bukan salahku, Tan.”
“Pergilah ke kota, ini urusanmu, Wan.”
Wan tiba-tiba takut. Ia khawatir korban akan semakin bertambah dan bersikap lebih arogan lagi. Lantas ia pergi meninggalkan orang-orang yang mengadu padanya dengan alasan akan kembali bekerja menjaga rakit. Lalu tanpa sengaja dilihatnya seorang penumpang rakit dari kota membawa sebuah koran harian ternama. Wan lemas saat membaca headline harian tersebut, Usai Balimau Tubuh Gata-gatal, Warga Rumbio Tuntut Jaminan Kesehatan.


 11.53
11.53
 immfaijakseluhamka
immfaijakseluhamka

 Posted in:
Posted in: 







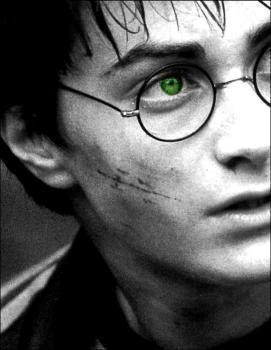
0 komentar:
Posting Komentar